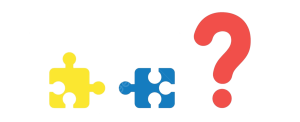“Halo Ran, btw, aku udh proses gugat cerai.. Udah ada pemanggilan sidang pertamanya”, sebuah kalimat muncul di layar HPku beberapa hari yang lalu.
Kaget? Ya. Sedih? Pasti ada sedihnya, apalagi berita itu datang dari kerabat dekat. Banyak memori masa lalu yang tak (mungkin) bisa hilang dari ingatan. Sejenak badanku bergetar dan air mataku menetes. Tak lama, tak apa. Sudah biasa reaksi tubuhku begitu. Cukup dirasakan dan dibiarkan berlalu saja.
“Divorce” atau perceraian saat ini mungkin sudah tidak terlalu “asing” bagi kita. Kakakku, temanku, sepupu-sepupuku dan aku sendiri sudah mengalaminya. Buatku, perceraian bukanlah jalan yang baik (untuk dipilih), tapi juga bukanlah yang terburuk. Pada momen apapun ketika saya dimintai pendapat, saya selalu mempercayakan keputusannya kepada yang bersangkutan. Saya hanya akan memberikan pandangan plus minusnya saja.
Ada di sebuah kasus, teman saya bertahan di pernikahan yang sangat toxic tapi bertahan demi harta. Ada juga kasus yang sedang viral, walau sudah babak belur hampir mati, tapi tetap bertahan demi anak. Buat saya yang tidak ada salahnya, karena memang itu adalah hak dia untuk memilih keadaannya dengan segala plus minusnya.
Pesan saya hanya satu, apapun itu, lakukanlah dengan kesadaran. Ada baiknya memisahkan emosi sebelum bertindak atau memutuskan. Menyendiri itu ada baiknya. Jika sudah tenang, berhentilah menyakiti. Baik diri sendiri, ataupun orang lain. Pilihlah keputusan yang paling tidak menyakiti. Ingat, diri sendiri juga salah satu yang harus kita pikirkan. Kalau kita juga tersakiti, bisa jadi kita akan menyakiti banyak pihak dalam bentuk berbeda.
Doa baik untuk semua yang sedang berjuang.
Aku yakin, kalian melangkah dengan segala pertimbangan dan usaha yang telah kalian tempuh.
Semoga kalian dikuatkan, dilancarkan, dan diberikan kemudahan kebahagiaan pada kehidupan setelahnya. Allah Maha Baik, insyaAllah akan selalu aja jalan untuk niat-niat baik.