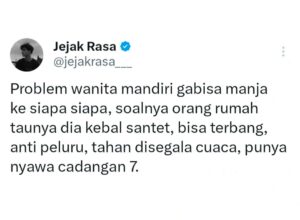Beberapa waktu lalu saya dan kedua teman saya pergi ke Bangkok untuk melihat konser Imagine Dragons. Walau awalnya saya tidak terlalu hafal lagu-lagunya (tapi suka sih), tapi saya cukup bersemangat mengingat beberapa konser band luar biasanya cukup bagus dari segi setting dan sound-nya, lebih lagi di Bangkok saya sudah menyiapkan beberapa coffee shops untuk dikunjungi.
 Terakhir ke Bangkok tahun 2019, rasa-rasanya tidak banyak berubah ternyata kota ini. Masih seperti Jakarta yang semi kumuh di beberapa sudut kotanya, kabel listrik serumit hidup dan banyak Tuk Tuk kebut-kebutan di jalan. Masih panas, masih agak berantakan, masih juga bikin saya bingung ketika ketemu “cewek” harus manggil “mam” atau “sir”.
Terakhir ke Bangkok tahun 2019, rasa-rasanya tidak banyak berubah ternyata kota ini. Masih seperti Jakarta yang semi kumuh di beberapa sudut kotanya, kabel listrik serumit hidup dan banyak Tuk Tuk kebut-kebutan di jalan. Masih panas, masih agak berantakan, masih juga bikin saya bingung ketika ketemu “cewek” harus manggil “mam” atau “sir”.
Kuliner masih sama enaknya! Serius, enak-enak semua, dan masih terjangkau. Buahnya super-super. Ada satu kuliner yang belum pernah saya coba yaitu makanan-makanan mengandung ganja yang dijual legal. Saya bilang ke teman saya “Mbul, nyoba yuk!”, jawabannya “nggak boleh! Sedang banyak hal yang ingin kita doakan, nanti nggak dikabulin kalau nakal.”
 Berbeda dengan konser Ed Sheeran di 2019 lalu, konser Imagine Dragons ini diadakan di Queen Sirikit National Convention Center. Kami datang mepet jam manggung, karena di konser Ed Sheeran sebelumnya saya dan Ully datang 6 jam sebelumnya dan mati kutu nungguinya haha.
Berbeda dengan konser Ed Sheeran di 2019 lalu, konser Imagine Dragons ini diadakan di Queen Sirikit National Convention Center. Kami datang mepet jam manggung, karena di konser Ed Sheeran sebelumnya saya dan Ully datang 6 jam sebelumnya dan mati kutu nungguinya haha.
Konsernya menyenangkan karena padat berisi, tidak ada band pembuka, tidak ada MC. 12 lagu dari 13 song list saya dinyanyikan, jadi full senyum kaya karaokean 😀
Sound sysyem bagus, live performance bagus, penonton tertib, so happy!
Buat saya, sebuah kebahagiaan untuk bisa melihat beberapa musisi secara langsung dengan kehiruk-pikukannya. Masih selalu menyempatkan, bahkan mengajak Ken buat ikut nonton. Mungkin saya termasuk extrovert ya? Karena saya sangat menikmati live music, walau beresiko kesamber energi banyak orang hahaha. Terkadang teman-teman seumuran saya heran, “Masih punya energi ya Ran buat nonton konser? Kalau aku mending tidur deh, kan sama aja liat di youtube!”
Enggak tau ya, tapi saya tuh masih bisa loncat-loncat hlo kalau nonton konser. Mungkin saya kadang suka kelebihan energi ya. Saya juga tipikal yang agak cuek walau mungkin penonton-penonton lain mbatin “Ini tante-tante heboh banget dah!” hahaha 😀
—